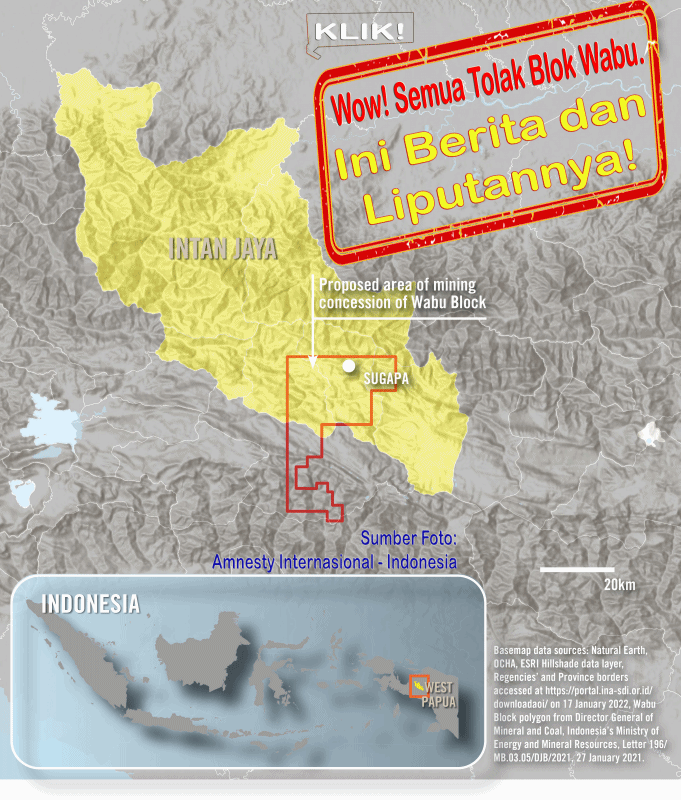|
| Bagian Depan Pabrik Daging, tempat Sidratul (WNI) bekerja, dikota Bourke, negara bagian New South Wales, Australia. Foto: Document pribadi Sidratul M. |
Oleh: Sidratul
Muntaha *
*) Buruh WNI di Australia
Bau amis menusuk hidung saya ketika pertama kali menginjakkan kaki di Slaughter Floor — ruangan tempat saya bekerja di pabrik daging di Bourke.
Dari depan pabrik bau daging memang sudah terendus. Namun, bau yang saya cium di dalam Slaughter Floor bukan sekadar menyengat. Sekali dua kali, saya juga pernah melihat kotorannya terburai dari jeroan yang bocor tanpa disengaja, diiringi teriakan ‘O’ panjang orang-orang sekeliling saya. Sama seperti penampakannya, bau kotoran itu tak sedap bukan main.
Untungnya
saya cepat terbiasa dengan hal itu. Hanya saja, tetap ada bagian yang membuat
tegang.
Utamanya
suasana Slaughter Floor yang terasa sangat efisien dan konstan. Setiap hewan
digantung di sebuah pengait dan digerakkan oleh mesin sehingga hewan-hewan itu
bisa diproses bergilir oleh para pekerja. Masing-masing pekerja punya tugas
yang spesifik: menyembelih hewan; menguliti kaki depan dan pundak; melepas
kulit bulat-bulat dari tubuh hewan; mengiris buntut; memisahkan jeroan dari
perut; memotong leher; dan lain sebagainya.
Sesekali
kepanikan terjadi. Tak lama setelah masuk ruangan, misalnya, saya melihat
seseorang mengejar kambing yang lewat dari hadapannya dan belum selesai ia
garap. Sambil mengikuti kambing yang terus ‘berjalan’, ia mengiris-iris bagian
tubuh hewan itu yang entah apa.
Untung
saja ia bisa menyelesaikan garapannya sebelum kambing itu sampai ke pekerja
lain. Kalau tidak, biasanya mesin yang menggerakkan pengait bakal distop. Dan
sebagai anak baru saya ngilu membayangkan perasaan canggung seorang pekerja
yang menjadi penyebab satu ruangan berhenti beroperasi meski hanya beberapa
detik.
Jangan
tanya apakah saya pernah bikin Slaughter Floor berhenti beroperasi atau tidak.
Kalian pasti tahu jawabannya. Dan akan saya ceritakan setelah ini.
Hari
pertama bekerja saya lalui dengan mudah, itupun tak penuh delapan jam.
Pasalnya, dari pagi sampai siang, saya masih harus menunggu vaksin supaya saya
tak terkena penyakit akibat terus-menerus berinteraksi dengan
hewan ternak. Setelah itu pun saya dan pekerja baru mesti melewati semacam
fase pengenalan perusahaan.
Isinya
sebenarnya formalitas saja, tapi saya tetap ngangguk-ngangguk ketika tahu bahwa
perusahaan tersebut hanya memproses daging halal, tidak ada babi. Selain pabrik
di Bourke, perusahaan tersebut juga punya pabrik di tiga kota lain. Mereka juga
punya peternakan. Ada pula kantor buat distribusi di berbagai negara. Paling
jauh agaknya ada di Kanada dan China.
Bisa
dibilang perusahaan ini cukup besar, meski mereka menyebutnya sebagai ‘family
owned’ yang sempat membuat saya berpikir ia berskala kecil belaka. Setelah
tiga hari kerja, skala perusahaan itu terasa semakin besar setelah tahu ada
4000 kambing dan domba yang diproses di pabrik tempat saya bekerja. Setiap
hari.
Setelah
fase pengenalan itu barulah kami diberi perlengkapan: sepasang baju dan celana
berwarna putih; masker tebal sebab kami baru divaksin; penutup kepala supaya
rambut kami tak rontok di dalam ruang kerja; helm yang dilengkapi penutup
telinga sebab ruangan dipenuhi suara bising; sarung tangan kain juga sarung
tangan karet; dan apron dari plastik tebal berwarna putih.
 |
| Foto Saat Sidratul Muntaha berada di Kamar Mandi umum di Pablik. |
Usai
mengenakan perlengkapan itu, saya diantar ke bagian yang sering disebut sebagai
Buang Lambung oleh orang Indonesia di pabrik. Kerjaannya simpel, yakni membuang
jeroan yang terus berdatangan tanpa henti ke dalam cerobong yang terhubung
dengan ruangan lain.
Hanya saja
kerjaan itu mungkin tak akan cocok buat orang yang gampang jijik.
Kadang-kadang, ada jeroan yang bocor dan mau tak mau saya harus menyentuh
lambung yang berlumur cairan kuning. Herannya, meskipun menjijikkan, saya masih
sempat melihat telapak tangan saya sebelum mencucinya di wastafel yang selalu
tersedia di dekat pekerja.
Di luar
urusan kotoran kerjaan itu sebenarnya sangat ringan. Sayang, keesokan harinya
saya dipindah ke bagian hanging. Di bagian ini, saya menggarap
hewan yang baru saja dikuliti dan dadanya baru saja dibelah. Hewan-hewan itu
diantar ke tempat saya menggunakan gantungan yang digerakkan mesin.
Posisi
hewan itu, saat diantarkan ke hadapan saya, sesekali bikin saya bengong
sepersekian detik. Kaki depannya digantung sedang kaki belakangnya terkatung.
Dadanya yang sudah dibelek itu persis di depan mata saya. Cahaya lampu yang
masuk melalui celah dada itu, lantas meneranginya isinya meski samar-samar,
bikin saya kerap membayangkan jantungnya masih berdetak.
Tapi saya
tak boleh bengong terlalu lama sebab mesti melaksanakan tugas: menggantung kaki
belakangnya ke pengait baru yang juga diantar oleh mesin dari belakang saya.
Saya tak paham kenapa kaki belakangnya juga harus digantung sampai saya
memerhatikan orang yang memproses hewan setelah bagian saya. Mereka memotong
ujung kaki depan yang lebih dulu tergantung sehingga posisi kambing jadi
terbalik. Dengan begitu, bagian selanjutnya yang bertugas mengiris buntut jadi
lebih mudah.
Kembali ke
pekerjaan saya: sebenarnya ia tak sulit. Hanya saja, kerjaan itu punya tugas
tambahan yang seringkali merepotkan. Salah satunya, membenarkan pengait yang
terus berdatangan dari belakang saya, yang entah kenapa sering sekali
tersangkut di tengah jalan. Kalau sudah begitu, saya harus membetulkan pengait
itu cepat-cepat lalu kembali menggantung kaki kambing di depan saya.
Jujur,
saya bukan tipikal orang yang suka multitasking. Saya bisa
melakukannya kalau terdesak, tapi saya memilih menghindarinya sebisa mungkin.
Tapi alur kerja pabrik ini berkata lain. Saya tak jarang harus melakukannya dan
kemudian kesialan itu tiba.
Sebuah
pengait di belakang saya tersangkut dan susah sekali dibetulkan. Sambil
membetulkan pengait, saya tolah-toleh ke kambing yang terus berdatangan. Salah
satunya berlalu begitu saja seperti perisak tak tahu diri. Tetapi pengait yang
saya coba betulkan itu tak juga bergerak meski saya tarik-tarik. Pengait itu
baru bergerak kembali ketika kambing sudah mendekat ke bagian pengiris buntut.
Lintang pukang saya kejar kambing perisak itu dan mencoba menggantung kakinya
sekali tapi gagal. Saya coba lagi untuk kedua kali tapi makin sulit karena
kambing itu mulai bergerak ke tempat lebih tinggi. Kakinya pun licin karena
darah. Beberapa kali kaki itu lolos dari tangan saya ketika mau saya gantung.
Seorang perempuan lantas datang membantu saya mengangkat kambing itu tapi tetap
tak bisa. Tak lama, ada teriakan dari belakang saya: “Stop!”
Seketika
mesin penggerak pengait itu berhenti dan kami bisa menggantungnya dengan
sedikit tenang.
Tak lama,
ada pria berbadan bongsor mengenakan seragam berbeda dari yang lain. Ia berdiri
di depan saya. Dia tak berkata apa-apa dan karenanya saya kira ia melihat
kambing yang saya gantung. Mesin lantas bekerja kembali dan pria itu masih
berdiri menatap saya. Hampir 5 menit.
Tatapannya
macam Medusa tapi memiliki efek yang berbeda. Alih-alih membeku, saya bekerja
macam orang kesetanan. Sambil bergerak cepat saya mendesis … bajingan.
Hari
ketiga, agaknya, saya mulai terbiasa. Melihat saya bekerja lebih cepat, pria
berbadan bongsor yang kemarin menatap saya mengangguk-angguk dan memberi
jempol. Londo ini pintar juga apresiasi orang, pikir saya.
Tapi saya
mulai punya masalah dengan kaki. Karena berdiri 8 sampai 9 jam, kaki saya
terasa sakit sesampainya di rumah, bikin jalan saya agak pincang.
Selain
itu, tak lagi ada hambatan berarti. Apalagi, di hari ketiga, saya sempat
dibantu oleh seorang teman asal Tangerang yang sudah hampir 9 bulan kerja di
pabrik ini. Mari kita sebut ia Senior. Ia sebenarnya bekerja di bagian chiller,
namun hari itu dia disuruh membantu saya setengah hari setelah mengeluh
punggungnya sakit. Alhasil, saya bisa fokus menggantung kambing sedang dia
sesekali membantu kalau saya tiba-tiba harus membetulkan pengait yang
tersangkut atau sebaliknya.
Teman ini
dulunya juga bekerja di bagian hanging, sama seperti saya.
Konon dia baru terbiasa setelah bekerja dua minggu. Dan cara bekerjanya pun
berbeda dengan orang yang pertama kali mengajari saya menggantung kaki, yakni
seorang lelaki asal Jepang. Mari kita sebut saja ia Senpai.
Senpai ini
bekerja dengan sangat rapi tapi cepat. Sebelum menggantung kambing jantan, ia
selalu membetulkan posisi kelamin kambing itu. Lalu sehabis menggantung dua
kambing, ia selalu mencuci tangan di wastafel yang cuma berjarak dua langkah
dari kami. Saat itu saya simpulkan ia seorang perfeksionis. Dan saya menurut
saja ketika ia menyuruh saya mengikuti metodenya itu, meskipun metode itu
beberapa kali bikin saya hampir kena sial.
Satu
waktu, saat mau membetulkan posisi kelamin kambing, salah satu bagiannya sangat
lengket dan tak mau lepas dari tangan saya. Prosesi menggantung kaki lantas
jadi terhambat karena saya terdistraksi urusan kelamin. Untung saja kambing itu
belum sampai berlalu terlalu jauh. Saya masih tak masalah.
Saya baru
merasa kesal ketika melihat metode kerja Senior yang memang jauh lebih senior
dari Senpai. Ia cuci tangan cuma sesekali. Ia juga tak pernah membetulkan
posisi kelamin kambing sebelum menggarapnya.
Menjelang
sore hari, ketika Senpai disuruh membantu saya menggantikan Senior, saya mulai
berani melakukan pemberontakan kecil-kecilan. Saya menolak membetulkan posisi
kelamin kambing jantan sebelum menggantung kakinya. Sudah punya dua
jobdesk kok masih disuruh ngurus peler kambing? Betapa pelernya!
Endingnya
saya menggantung kaki kambing semau saya saja. Yang penting pengaitnya saya
tusuk di kaki, bukan di burit. Jadilah saya bisa bekerja sambil bengong,
sesekali berpikir mau menulis apa, lebih sering lagi membandingkan kambing yang
satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang ada kambing bunting yang berat dan
bikin saya sedikit repot menggantungnya. Kadang-kadang ada kambing yang
jeroannya besar sekali macam orang sembelit. Ada juga kambing jantan yang punya
tiga biji.
Memperhatikan
hal-hal macam itu mungkin tak ada gunanya, tapi lebih baik daripada
terus-menerus menengok jam dinding. Lagipula, saya tak biasa ngobrol sambil
kerja.
Lalu
tiba-tiba kambing sudah habis, berganti domba. Domba biasanya hanya sedikit,
tapi beratnya nauzubillah. Kalau pekerjaan di pabrik ini
diibaratkan gim, maka domba ini seperti musuh terakhir dan kambing hanyalah
kroco.
Untungnya
jumlah domba selalu lebih sedikit. Alhasil, tak terasa hewan yang saya gantung
sudah habis. Edan. Saya menggantung hampir 4000 hewan hari itu. Dan mungkin
hari-hari setelahnya juga.
Setelah
itu, saya pulang dan bersih-bersih. Penghujung hari tinggal cukup buat dipakai
tidur dan masak buat bekal besok. Saya jadi berpikir ulang soal pencapaian yang
tadi saya bayangkan.
Saya sudah menggantung 4000 hewan, terus kenapa? Sudahlah, saya mau cepat-cepat gajian saja. [*]