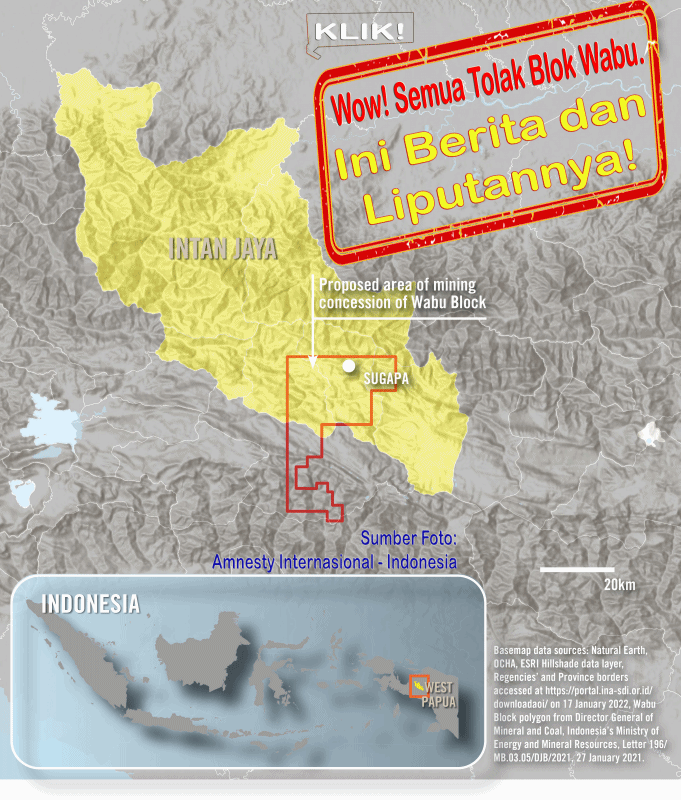Oleh Ruben Benyamin Gwijangge*)
Di MANA makna kemerdekaan bagi pengungsi di tanah Papua seperti pengungsi di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan di berbagai lekuk dan pesona bumi Cenderawasih?
Pertanyaan penting diajukan sebagai reflektif di saat masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote tengah bergembira merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Ahad 17 Agustus 2025.
Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan hari bersejarah: Proklamasi Kemerdekaan. Tahun ini, genap 80 tahun Indonesia merdeka. Di kota-kota besar, masyarakat menyambutnya dengan gegap gempita dengan upacara bendera.
Kemeriahan ini ditaburi dengan aneka perlombaan rakyat, konser musik hingga doa syukur di rumah ibadah. Bendera Merah Putih berkibar di setiap sudut jalan, simbol kebanggaan sebagai bangsa yang bebas dari penjajahan.
Namun, di balik keriuhan itu, ada satu suara lirih yang nyaris tak terdengar: suara pengungsi dari Nduga, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan lain-lain di tanah Papua. Bagi para pengungsi yang bertahan di hutan-hutan, gunung, bukit, lembah, bibir sungai, ngarai, dan lain sebagainya.
Suara lirih dan miris itu: kemerdekaan masih sebatas simbol di televisi atau buku sejarah. Di tanah pengungsian, mereka, para pengungsi di tanah Papua, justru bertanya dengan getir dalam dinding hati mereka yang polos dan lugu: di mana arti kemerdekaan bagi kami?
Luka yang Belum Sembuh
Sejak Desember 2018, Nduga menjadi salah satu episentrum konflik bersenjata di Papua. Insiden serangan di proyek Trans Papua memicu operasi militer besar-besaran. Kampung-kampung (desa) di Distrik Yigi, Mbua, Mugi, dan Paro menjadi saksi bisu kontak senjata yang berkepanjangan tanpa ujung.
Ribuan warga sipil terpaksa meninggalkan rumah mereka, mencari perlindungan ke Wamena, Lanny Jaya, Jayawijaya (Papua Pegunungan) bahkan Mimika di Provinsi Papua Tengah.
Hingga tahun 2025, pengungsian itu belum berakhir. Anak-anak Nduga tumbuh besar di tanah orang, tanpa kepastian kapan bisa kembali ke kampung halaman. Banyak yang putus sekolah. Perempuan kehilangan kebun yang menjadi sumber pangan utama. Warga lanjut usia (lansia) hidup dalam trauma yang tak kunjung reda.
Di pengungsian, mereka menggantungkan hidup pada bantuan gereja, keluarga atau organisasi kemanusiaan yang kemampuan dan sumber dayanya sangat terbatas. Bagi mereka, perayaan kemerdekaan dengan lomba panjat pinang atau upacara bendera terasa jauh dan asing. Yang mereka rindukan hanyalah rumah, kebun, dan tanah leluhur.
Di kota-kota besar, kemerdekaan berarti kebebasan berpendapat, akses pembangunan, dan peluang ekonomi. Namun, bagi pengungsi Nduga, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan wilayah lain di tanah Papua, kemerdekaan berarti hal yang paling sederhana sekaligus paling mendasar: hak untuk pulang dan hidup dengan aman dan tenang di kampung.
Seorang pengungsi dari Distrik Paro, Ipolus Gwijangge, dalam nada getir dan jujur, lidahnya kelu. Suara miris berkelebat tertahan di rongga dada. Salah satunya, “kalau mereka (TNI-Polri) mengosongkan Paro, baru kami mau balik ke sana, itu kami bisa hidup tenang.”
Ungkapan ini menggambarkan paradoks kemerdekaan di Papua. Indonesia sudah merdeka 80 tahun, tetapi sebagian rakyatnya masih belum bisa menikmati kemerdekaan dari rasa takut.
Negara dan Warga: Siapa yang Dilindungi
Pemerintah pusat menekankan pembangunan infrastruktur sebagai wujud perhatian terhadap Papua: jalan Trans Papua, bandara, jembatan, gedung pemerintahan, hingga proyek food estate.
Namun, bagi pengungsi Nduga, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan wilayah konflik lain di tanah Papua, semua itu tidak menjawab pertanyaan paling mendasar: kapan kami bisa pulang ke Kampung kami dan hidup dengan aman?
Bantuan kemanusiaan memang ada, tetapi sifatnya sporadis dan tidak berkelanjutan (sustainable). Pun tidak ada mekanisme pemulangan pengungsi yang jelas, apalagi jaminan keamanan di kampung asal mereka. Bahkan, misalnya, jumlah pengungsi Nduga pun tidak memiliki data resmi yang pasti —sebuah kelalaian serius dari negara yang seharusnya hadir melindungi setiap warga.
Ironisnya, peran terbesar justru dimainkan oleh gereja-gereja. Gereja Kristen Indonesia (GKI), Gereja Kemah Injil di Tanah Papua (Kingmi), Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua, Gereja Katolik, dan denominasi lain membuka pintu bagi para pengungsi.
Mereka menyediakan tempat berlindung, makanan, dan pendidikan darurat. Gereja menjadi benteng terakhir kemanusiaan ketika negara sibuk dengan pendekatan keamanan. Pertanyaan penting muncul: apakah negara benar-benar melindungi seluruh rakyatnya atau hanya mereka yang sejalan dengan narasi resmi tentang Papua?
Untuk memahami mengapa konflik dan pengungsian seperti di Nduga, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan wilayah lain di bumi Cenderawasih, terus berulang, kita tidak bisa hanya melihat pada peristiwa 2018 atau 2023.
Akar masalahnya jauh lebih dalam, yaitu perbedaan penafsiran sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.
Bagi pemerintah Indonesia, Pepera sudah final dan sah menjadi dasar hukum internasional untuk memasukkan Papua ke dalam NKRI. Tetapi bagi banyak orang asli Papua, Pepera adalah tragedi politik karena hanya 1.026 orang yang dipilih untuk mewakili ratusan ribu rakyat, di bawah tekanan militer, jauh dari prinsip demokrasi satu orang satu suara (one man one vote).
Luka sejarah ini diwariskan lintas generasi kemudian melahirkan kecurigaan, resistensi, dan konflik yang tak kunjung usai. Pengungsian Nduga dan ribuan pengungsi lainnya di Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan wilayah lain di tanah Papua yang disaksikan rakyat dan negeri yang tengah merayakan HUT ke-80 saat ini, hanyalah salah satu manifestasi dari persoalan politik yang lebih besar.
Jalan Damai yang Bermartabat
Selama akar masalah politik ini tidak disentuh, pengungsian dan kekerasan akan terus berulang. Bantuan kemanusiaan penting, tetapi tidak cukup. Pembangunan infrastruktur diperlukan tetapi tidak menyembuhkan luka sejarah.
Karena itu, solusi yang paling mendasar adalah membuka dialog damai dan perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai representasi politik rakyat Papua.
Dialog ini tidak boleh sebatas formalitas, melainkan sebuah proses yang tulus, setara, dan berlandaskan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.
Model ini bisa mencontoh Perjanjian Helsinki 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Setelah puluhan tahun konflik, perundingan itu berhasil mengakhiri kekerasan, memberikan ruang politik baru, dan memulihkan kepercayaan rakyat Aceh terhadap negara.
Jika hal serupa bisa dilakukan di Papua, maka pengungsi Nduga, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan wilayah lain di tanah Papua bukan hanya akan kembali ke rumah, tetapi juga ke sebuah masa depan yang lebih damai dan adil.
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka adalah pencapaian besar. Tetapi, kemerdekaan sejati tidak hanya diukur dari lamanya bendera berkibar, melainkan sejauh mana setiap warga negara merasakan perlindungan, keadilan, dan damai.
Bagi pengungsi Nduga, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan wilayah konflik lain di tanah Papua, arti kemerdekaan bukanlah upacara dan pernak-pernik Merah Putih di sudut bangunan atau lomba panjat pinang.
Arti kemerdekaan adalah rumah yang bisa mereka tinggali kembali, kebun yang bisa mereka tanami lagi, sekolah yang bisa dibuka untuk anak-anak mereka, dan yanah leluhur yang bisa mereka jaga dengan aman.
Selama pertanyaan: di mana arti kemerdekaan bagi kami? masih menggema dari tanah pengungsian, Indonesia masih punya pekerjaan rumah besar, yaitu mewujudkan damai yang adil dan bermartabat bagi seluruh rakyatnya, termasuk Papua.
Bila hal tersebut belum terwujud, gerak langkah negara meraih masyarakat yang aman dan sejahtera masih utopis. Ia masih jauh dari makna kemerdekaan yang hakiki di saat usianya menyentuh angka 80 tahun.(*)
Penulis adalah Mahasiswa Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua





















.jpeg)