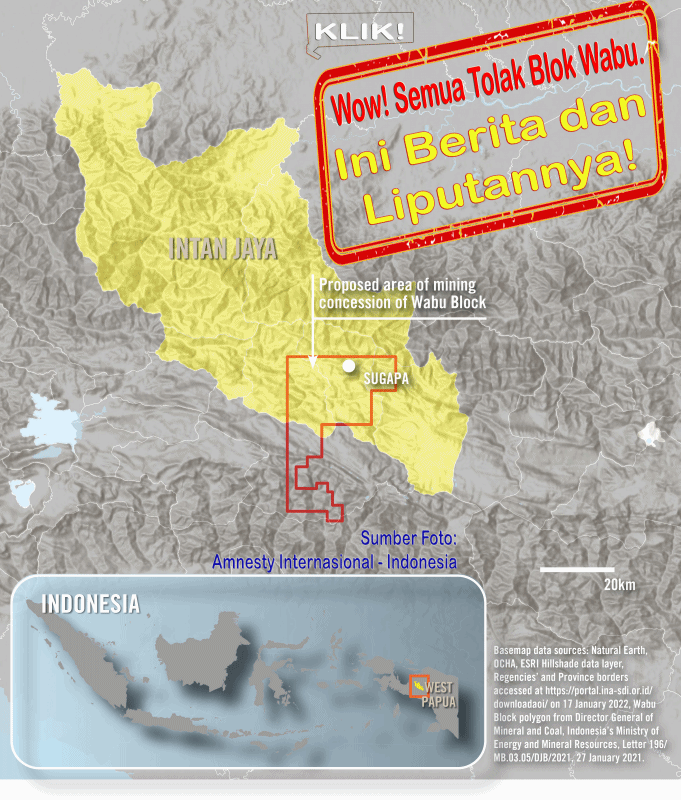Oleh: Wallo
Hujan gerimis di luar kos seperti mengetuk-ngetuk malam. Maga duduk di tepi tempat tidur, kaki telanjang menjejak lantai dingin. Rambut gimbalnya yang acak dibiarkan menutupi sebagian wajah. Matanya terpaku pada layar gawai yang menampilkan foto seorang pria di beranda Facebook.
"Ih... kok bisa muncul lagi?" batinnya terguncang. Sosok itu—yang pernah jadi pusat hidupnya—kembali hadir, seakan menertawakan usahanya melupakan.
Namanya Maga, perempuan asal Paniai, lahir di Wamena. Hidup di kamar kos sempit, dengan dinding yang menyimpan aroma lembap hujan. Pria di foto itu adalah Wiyai, laki-laki yang dulu mencintainya, lalu menghilang tanpa alasan yang bisa masuk akal bagi hatinya.
Seharusnya ia sudah tenang, memulai lembaran baru. Tapi setiap kali mencoba, hatinya seperti diikat rantai tak kasatmata. Di malam-malam tertentu, ia duduk bersila di depan patung Bunda Maria, memohon agar wajah itu tidak lagi hadir di dalam mimpinya. Namun, di sisi lain, ia tahu: ia merindukannya dengan seluruh jiwa.
"Kalau mau datang, datang saja. Hati ini, cinta ini, semua ini milik ko sejak awal. Kalau mau pergi, pergi saja," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar.
Keheningan pecah oleh tangisnya sendiri. Bahunya berguncang, jemarinya menggenggam erat rosario. "Ini menyiksa sa betul..."
***
Dulu, Wiyai adalah mahasiswa kedokteran semester akhir. Tenang, ramah, dan penuh tanggung jawab. Banyak perempuan mendekatinya—bahkan seorang anak anggota DPR RI pernah menawarkan mobil Triton demi perhatiannya. Tapi Wiyai memilih Maga, bukan karena harta, melainkan karena kesederhanaan yang ia lihat dalam diri gadis itu.
Mereka bersama selama dua tahun. Hingga suatu sore, Wiyai jatuh sakit. Tiga minggu ia bertahan di kos. Maga akhirnya membawanya ke RS Dian Harapan, Dok 2, Jayapura. 2 minggu mereka di sana. Tak ada keluarga yang datang, hanya Maga yang setia duduk di samping ranjang.
"Maga, sa mau pangku kepala di ko paha. Boleh?"
Maga mengangguk, tangannya tetap sibuk menganyam noken bermotif Bintang Kejora.
"Nanti kalau kita wisuda, kita langsung ke Wamena lihat mama di sana ee?" Wiyai tersenyum, matanya setengah terpejam.
"Baru ko su beritahu keluarga di kampung?" tanya Maga pelan. Wiyai diam, bibirnya tak bergerak.
Tak lama kemudian, dokter masuk. Maga membangunkannya, tapi Wiyai tak merespon. Kakinya dingin. Dokter memeriksa nadinya, lalu dengan langkah cepat keluar memanggil tim medis.
Beberapa menit kemudian, seorang perawat berkata lirih, "Ade, mohon maaf, pasien su pergi."
Dunia Maga runtuh dalam satu kalimat itu.
***
Bulan-bulan berlalu. Hari wisuda tiba. Jayapura dipenuhi tawa, toga, dan pesta syukuran. Di setiap asrama ada musik dan goyang. Tapi Maga hanya duduk di kamar kos, memandangi toga yang terlipat rapi.
"Sa harus ke Intan Jaya. Harus ketemu nenek dan adiknya, Frans," tekadnya sambil mengemasi pakaian.
***
Perjalanan ke Intan Jaya bukan perkara mudah. Jalan licin, udara menusuk tulang, dan cerita-cerita tentang perang membuat setiap langkah berat. Setibanya di sana, ia mencari Pastor Paroki, satu-satunya orang yang mungkin tahu di mana keluarga Wiyai berada.
Pastor menghela napas panjang sebelum bicara.
"Jadi begini, adik... Seminggu sebelum Wiyai jatuh sakit, perang pecah di Homeo, distrik tempat nenek dan adiknya tinggal. Pesawat TNI membombardir wilayah itu. Rumah mereka terbakar habis. Nenek dan Frans ikut tiada."
Suara pastor mengambang di udara. Maga terdiam, matanya membesar, air mata mengalir tanpa ia sadari.
"Wiyai tahu semua ini," lanjut pastor, "tapi ia memilih tidak memberitahumu. Ia memendamnya sampai akhir."
Malam itu, Maga duduk di depan gereja, memandangi langit gelap. Hujan kembali turun, seolah ingin menyembunyikan air matanya. Dalam hati, ia berbisik kepada lelaki yang tak pernah benar-benar pergi:
"Ko sudah pergi, tapi sa akan bawa cerita ini pulang."
Tamat
* Penulis adalah pemuda pengangguran di Nabire